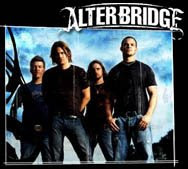Oleh Indra J. Piliang, 22-06-2007 21:02
DUA tokoh pembina partai politik dari dua partai berbeda, Surya Paloh (Partai Golkar) dan Taufik Kiemas (PDIP),bertemu di Medan.Pertemuan ini mendadak menimbulkan spekulasi politik, terutama dengan adanya sinyal-sinyal tentang koalisi, aliansi,atau sebutan lainnya. Kepiawaian Surya-Taufik dalam membangun sentimen politik telah memicu kalkulasi serius, antara lain dengan menyebut tahun 2009 sebagai sasar
 an strategis dan delegitimasi kekuasaan Presiden Yudhoyono sebagai titik pertaruhan. Kalau dirunut ke belakang, pertemuan Golkar dengan PDIP ini sudah terjadi beberapa kali pada tahun 2007 ini. Akhir Januari, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla bertemu dengan Sekjen PDIP Pramono Anung di New Delhi, India. Setelah itu, Kalla juga berjumpa Taufik Kiemas dalam acara yang digelar GP Ansor pada akhir Juni.Fasilitator pertemuan adalah Ketua Umum GP Ansor yang baru lengser dari kabinet, Saifullah Yusuf. Dua pertemuan ini diliput oleh pers. Setahu penulis, sudah terdapat sejumlah pertemuan tertutup lain yang tidak diketahui pers yang melibatkan petinggi partai. Artinya, pertemuan di Medan yang mulai melibatkan bendera-bendera kedua partai, berikut kaderkadernya, menunjukkan bahwa sudah ada kerja sama politik yang berjalan dengan baik. Artinya,kita tidak perlu merasa terkejut atas pertemuan-pertemuan itu, bahkan juga pertemuanpertemuan berikutnya. Berbeda dengan pembentukan Koalisi Kebangsaan pada waktu perebutan posisi pimpinan DPR 2004–2009 yang digagas oleh Akbar Tandjung, Megawati Soekarnoputri, Hamzah Haz, dan Abdurrahman Wahid, pergerakan politik sekarang dinakhodai pelaku-pelaku politik yang lebih profesional. Elemen struktural partai politik lebih banyak dilibatkan, tanpa perlu memicu keguncangan politik. Arena uji coba ketahanan koalisi politik baru ini secara riil dapat dilihat dalam proses pemilihan Gubernur Banten dan Gubernur DKI Jakarta. Dengan idiom-idiom ”NKRI, Pancasila, dan UUD 1945”, terlihat koalisi baru ini lebih berupaya menyatukan visi dan misi terlebih dulu ketimbang kepentingan politik jangka pendek dan menengah. Penggunaan idiom-idiom itu bisa mengarah kepada politik ideologis, yakni berdasarkan politik aliran yang pernah muncul sejak pembentukan UUD oleh Dewan Konstituante hasil pemilu 1955. Tiga Kerja Sama Konfigurasi politik tentu akan mengalami perubahan jika pertemuan Golkar-PDIP ini diteruskan dalam konteks yang lebih luas.Tatanan nasional dan internasional Indonesia juga mendapatkan pengaruh, mengingat kedua partai memiliki pengikut di kalangan masyarakat Indonesia secara hampir merata,tanpa mengenal kelas sosial, etnis, agama, ataupun tingkat pendapatan. Kedua partai politik juga mengendalikan pemerintahan lokal lewat kepala-kepala daerah. Untuk itu, mereka merasa perlu bekerja sama dalam bentuk yang lain. Pertama dalam merancang paket undang-undang bidang politik. Ada kebutuhan kedua partai politik ini untuk mempertahankan dominasi dalam sistem politik Indonesia sehingga terdapat kepentingan yang sama dalam mengajukan pasal-pasal atau ayat-ayat yang memberikan keuntungan maksimal. Penerapan sistem proporsional terbuka tanpa nomor urut dengan batas minimal 25% dari bilangan pembagi pemilih dan syarat dukungan lebih dari 25% suara pemilu legislatif bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah bentuk dari kepentingan yang sama itu. Kedua, dalam mengawal konsepsi kebangsaan yang sudah menjadi bagian integral perjalanan kedua partai, terutama tekanan ke arah nasionalisme, sekularisme, dan pluralisme. Soekarnoisme dan Soehartoisme dalam bidang politik di Indonesia memiliki kesamaan dengan Attaturkisme di Turki. Dalam masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, dukungan tentara di bidang politik menjadi perlu, tetapi sekarang justru masuk dalam lapangan politik praktis. Penyingkiran gerakan-gerakan separatis, penangkalan fundamentalisme religius, dan homogenisasi pemikiran, telah menjadi manifestasi dari pengawalan itu. Ketiga, kewaspadaan kepada pengaruh regionalisme dan globalisme yang pada gilirannya membenamkan Indonesia sebagai bangsa yang tidak memiliki martabat. Sikap kritis terhadap apa yang mereka sebut sebagai ”intervensi Amerika Serikat”dalam sejumlah soal, termasuk dalam kasus Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB, telah memicu kerja sama kedua partai ini dalam interpelasi. Persoalan Blok Ambalat dan masalah perbatasan dengan Timor Leste akan menjadi titik-titik penting bagi semangat kritis yang dibangun kedua partai politik ini. Penyamaan visi, misi, dan persepsi pada–minimal–ketiga hal itu terbaca dari serangkaian pernyataan para tokoh kedua partai politik. Begitu pula termuat dalam rekomendasi-rekomendasi rapatrapat kerja nasional dan kiprah politikus keduanya di parlemen. Kepercayaan diri yang tinggi sebetulnya terjadi dalam level pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, yakni keduanya menjadi mayoritas absolut. Tidak mengherankan kalau keduanya tidak mengambil panggung-panggung politik nasional, melainkan seperti hinggap dari satu pulau ke pulau lain untuk mengayunkan kanvas politik. Konfigurasi Baru Paparan itu memperlihatkan bahwa kedua partai dan tokohtokohnya tidak lagi memainkan pola politik populisme yang berbasiskan tokoh. Pola-pola pertemuan ”bilateral” yang dilakukan oleh Amien Rais dengan Yudhoyono atau antara Yudhoyono dengan Soetrisno Bachir dan lain-lain akan semakin ditinggalkan. Maka, menjadi jelas bahwa tokoh-tokoh seperti Soetrisno, berikut partai politiknya, PAN, sudah dengan sendirinya diabaikan. Begitu juga dengan PKS yang sudah ditempatkan berseberangan secara ideologis. PKB juga tidak diajak,terutama dengan tidak adanya lagi tokoh penting. PAN yang tidak bisa lepas dari bayang-bayang Amien, PKB yang dihuni terus oleh Abdurrahman Wahid dan PKS yang komunalistik dalam pengambilan keputusan, tentu kesulitan dalam membangun manuver politik ”secanggih” Golkar dan PDIP ini. Sekalipun partai-partai ini membentuk koalisi ideologis semacam ”keluarga Masyumi”, tetap saja lebih banyak mengandung benih perpecahan,daripada persamaan. Begitu pun Partai Demokrat yang berpolitik untuk Yudhoyono dan kekurangan sumber daya manusia yang punya talenta, tentu hanya dianggap sebagai ”kerumunan”. Partai yang terlalu cepat besar dalam perolehan dukungan pemilih ini memiliki kelemahan secara organisasional. Partai ini juga tidak dibiarkan melakukan manuver politik secara otonom, di luar pengaruh Yudhoyono, misalnya dalam kasus penarikan kembali dukungan ke arah amandemen UUD yang dirancang DPD RI. PPP tentu bisa menjadi penyeimbang secara ideologis,terutama dengan kehadiran kaum profesional dalam jajaran fungsionarisnya. PPP juga sudah pernah ”akrab” secara politik dengan Golkar dan PDIP, terutama kalau melihat pada patokan hari ulang tahun ketiga partai yang melebihi angka 30 tahun. Sehingga,terlihat sekali betapa PPP adalah partai yang paling tidak banyak dimusuhi dan paling mudah berteman dengan partai politik manapun. Dengan konfigurasi itu, terasa memang pola lama hadir kembali. Tidak ada yang benar-benar baru. Yang menarik tentu masing-masing tokoh politik,yang notabene bukan tokoh-tokoh ideologis, sudah mulai kembali ke basis ideologi partai. Terlepas dari proses rekayasa menurut aturan perundang-undangan yang dilakukan, kembalinya tokohtokoh partai pada pikiran-pikiran dasar semacam nasionalisme, telah menandakan bahwa partai bukan sekadar alat kekuasaan semata.(*)
an strategis dan delegitimasi kekuasaan Presiden Yudhoyono sebagai titik pertaruhan. Kalau dirunut ke belakang, pertemuan Golkar dengan PDIP ini sudah terjadi beberapa kali pada tahun 2007 ini. Akhir Januari, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla bertemu dengan Sekjen PDIP Pramono Anung di New Delhi, India. Setelah itu, Kalla juga berjumpa Taufik Kiemas dalam acara yang digelar GP Ansor pada akhir Juni.Fasilitator pertemuan adalah Ketua Umum GP Ansor yang baru lengser dari kabinet, Saifullah Yusuf. Dua pertemuan ini diliput oleh pers. Setahu penulis, sudah terdapat sejumlah pertemuan tertutup lain yang tidak diketahui pers yang melibatkan petinggi partai. Artinya, pertemuan di Medan yang mulai melibatkan bendera-bendera kedua partai, berikut kaderkadernya, menunjukkan bahwa sudah ada kerja sama politik yang berjalan dengan baik. Artinya,kita tidak perlu merasa terkejut atas pertemuan-pertemuan itu, bahkan juga pertemuanpertemuan berikutnya. Berbeda dengan pembentukan Koalisi Kebangsaan pada waktu perebutan posisi pimpinan DPR 2004–2009 yang digagas oleh Akbar Tandjung, Megawati Soekarnoputri, Hamzah Haz, dan Abdurrahman Wahid, pergerakan politik sekarang dinakhodai pelaku-pelaku politik yang lebih profesional. Elemen struktural partai politik lebih banyak dilibatkan, tanpa perlu memicu keguncangan politik. Arena uji coba ketahanan koalisi politik baru ini secara riil dapat dilihat dalam proses pemilihan Gubernur Banten dan Gubernur DKI Jakarta. Dengan idiom-idiom ”NKRI, Pancasila, dan UUD 1945”, terlihat koalisi baru ini lebih berupaya menyatukan visi dan misi terlebih dulu ketimbang kepentingan politik jangka pendek dan menengah. Penggunaan idiom-idiom itu bisa mengarah kepada politik ideologis, yakni berdasarkan politik aliran yang pernah muncul sejak pembentukan UUD oleh Dewan Konstituante hasil pemilu 1955. Tiga Kerja Sama Konfigurasi politik tentu akan mengalami perubahan jika pertemuan Golkar-PDIP ini diteruskan dalam konteks yang lebih luas.Tatanan nasional dan internasional Indonesia juga mendapatkan pengaruh, mengingat kedua partai memiliki pengikut di kalangan masyarakat Indonesia secara hampir merata,tanpa mengenal kelas sosial, etnis, agama, ataupun tingkat pendapatan. Kedua partai politik juga mengendalikan pemerintahan lokal lewat kepala-kepala daerah. Untuk itu, mereka merasa perlu bekerja sama dalam bentuk yang lain. Pertama dalam merancang paket undang-undang bidang politik. Ada kebutuhan kedua partai politik ini untuk mempertahankan dominasi dalam sistem politik Indonesia sehingga terdapat kepentingan yang sama dalam mengajukan pasal-pasal atau ayat-ayat yang memberikan keuntungan maksimal. Penerapan sistem proporsional terbuka tanpa nomor urut dengan batas minimal 25% dari bilangan pembagi pemilih dan syarat dukungan lebih dari 25% suara pemilu legislatif bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah bentuk dari kepentingan yang sama itu. Kedua, dalam mengawal konsepsi kebangsaan yang sudah menjadi bagian integral perjalanan kedua partai, terutama tekanan ke arah nasionalisme, sekularisme, dan pluralisme. Soekarnoisme dan Soehartoisme dalam bidang politik di Indonesia memiliki kesamaan dengan Attaturkisme di Turki. Dalam masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, dukungan tentara di bidang politik menjadi perlu, tetapi sekarang justru masuk dalam lapangan politik praktis. Penyingkiran gerakan-gerakan separatis, penangkalan fundamentalisme religius, dan homogenisasi pemikiran, telah menjadi manifestasi dari pengawalan itu. Ketiga, kewaspadaan kepada pengaruh regionalisme dan globalisme yang pada gilirannya membenamkan Indonesia sebagai bangsa yang tidak memiliki martabat. Sikap kritis terhadap apa yang mereka sebut sebagai ”intervensi Amerika Serikat”dalam sejumlah soal, termasuk dalam kasus Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB, telah memicu kerja sama kedua partai ini dalam interpelasi. Persoalan Blok Ambalat dan masalah perbatasan dengan Timor Leste akan menjadi titik-titik penting bagi semangat kritis yang dibangun kedua partai politik ini. Penyamaan visi, misi, dan persepsi pada–minimal–ketiga hal itu terbaca dari serangkaian pernyataan para tokoh kedua partai politik. Begitu pula termuat dalam rekomendasi-rekomendasi rapatrapat kerja nasional dan kiprah politikus keduanya di parlemen. Kepercayaan diri yang tinggi sebetulnya terjadi dalam level pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, yakni keduanya menjadi mayoritas absolut. Tidak mengherankan kalau keduanya tidak mengambil panggung-panggung politik nasional, melainkan seperti hinggap dari satu pulau ke pulau lain untuk mengayunkan kanvas politik. Konfigurasi Baru Paparan itu memperlihatkan bahwa kedua partai dan tokohtokohnya tidak lagi memainkan pola politik populisme yang berbasiskan tokoh. Pola-pola pertemuan ”bilateral” yang dilakukan oleh Amien Rais dengan Yudhoyono atau antara Yudhoyono dengan Soetrisno Bachir dan lain-lain akan semakin ditinggalkan. Maka, menjadi jelas bahwa tokoh-tokoh seperti Soetrisno, berikut partai politiknya, PAN, sudah dengan sendirinya diabaikan. Begitu juga dengan PKS yang sudah ditempatkan berseberangan secara ideologis. PKB juga tidak diajak,terutama dengan tidak adanya lagi tokoh penting. PAN yang tidak bisa lepas dari bayang-bayang Amien, PKB yang dihuni terus oleh Abdurrahman Wahid dan PKS yang komunalistik dalam pengambilan keputusan, tentu kesulitan dalam membangun manuver politik ”secanggih” Golkar dan PDIP ini. Sekalipun partai-partai ini membentuk koalisi ideologis semacam ”keluarga Masyumi”, tetap saja lebih banyak mengandung benih perpecahan,daripada persamaan. Begitu pun Partai Demokrat yang berpolitik untuk Yudhoyono dan kekurangan sumber daya manusia yang punya talenta, tentu hanya dianggap sebagai ”kerumunan”. Partai yang terlalu cepat besar dalam perolehan dukungan pemilih ini memiliki kelemahan secara organisasional. Partai ini juga tidak dibiarkan melakukan manuver politik secara otonom, di luar pengaruh Yudhoyono, misalnya dalam kasus penarikan kembali dukungan ke arah amandemen UUD yang dirancang DPD RI. PPP tentu bisa menjadi penyeimbang secara ideologis,terutama dengan kehadiran kaum profesional dalam jajaran fungsionarisnya. PPP juga sudah pernah ”akrab” secara politik dengan Golkar dan PDIP, terutama kalau melihat pada patokan hari ulang tahun ketiga partai yang melebihi angka 30 tahun. Sehingga,terlihat sekali betapa PPP adalah partai yang paling tidak banyak dimusuhi dan paling mudah berteman dengan partai politik manapun. Dengan konfigurasi itu, terasa memang pola lama hadir kembali. Tidak ada yang benar-benar baru. Yang menarik tentu masing-masing tokoh politik,yang notabene bukan tokoh-tokoh ideologis, sudah mulai kembali ke basis ideologi partai. Terlepas dari proses rekayasa menurut aturan perundang-undangan yang dilakukan, kembalinya tokohtokoh partai pada pikiran-pikiran dasar semacam nasionalisme, telah menandakan bahwa partai bukan sekadar alat kekuasaan semata.(*)